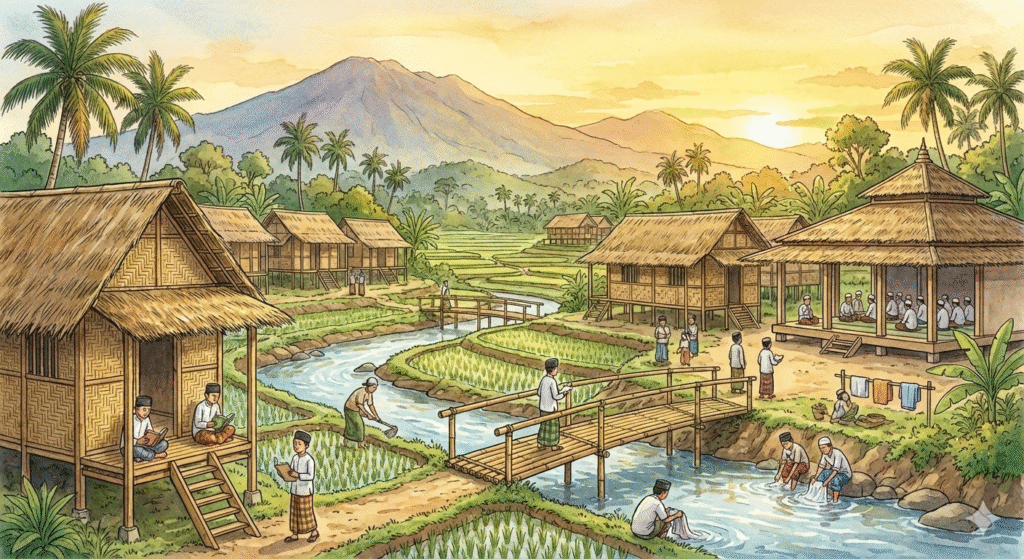
[Sumber gambar: AI]
Penulis: Jenida Nurinda Dustriani
Di masa pandemi COVID-19, ketika dunia terasa sunyi dan penuh ketakutan, saya justru menemukan kebersamaan yang tak terlupakan. Saya dan beberapa teman mengaji di dekat rumah saya, di sebuah kobong sederhana yang menjadi tempat kami berkumpul, menginap, dan menjalani hari-hari bersama. Di sana, kami seolah lupa bahwa di luar ada virus yang membatasi jarak. Tidak ada jaga jarak, tidak ada masker—yang ada hanya kebersamaan, tawa, dan rutinitas mengaji siang dan malam.
Banyak sekali kesan yang tertinggal selama kami tinggal di kobong. Susah dan senang kami jalani bersama. Kami belajar menghafal Al-Qur’an, mempelajari kitab-kitab, sekaligus belajar hidup mandiri jauh dari keluarga. Jika waktu bisa diulang, mungkin saya ingin kembali ke masa itu, masa di mana kebersamaan terasa begitu sederhana namun bermakna.
Suatu pagi, saya pergi ke warung dekat tempat pengajian untuk membeli keperluan masak dan jajan. Seusai dari warung, muncul ide iseng. Saya mengajak teman-teman berlari kembali ke kobong—siapa yang sampai duluan akan menjadi pemenang dan saya janjikan satu makanan. Tanpa banyak pikir, saya langsung berlari sekencang mungkin. Namun ternyata, tidak satu pun dari mereka ikut berlari.
Di depan saya, ada sekumpulan anak-anak yang sedang bermain. Tanpa saya duga, salah satu dari mereka menjahili saya dengan mengaitkan kaki. Seketika saya terjatuh keras. Tubuh saya terguling ke depan, kepala masuk ke dalam pasir bangunan, dan tangan saya menghantam aspal. Luka di tangan saya sangat parah hingga tulang bagian dalam terlihat. Sampai sekarang, bekas lukanya masih ada. Lebih memalukan lagi, guru ngaji saya melihat kejadian itu karena beliau sedang mengecat dinding rumahnya.
Malam harinya, saya tetap kembali mengaji meskipun tangan kiri saya tidak bisa digerakkan ke bawah. Selama hampir dua bulan, tangan itu harus selalu saya sanggah di pundak, seperti pose “sasageyo”. Rasa sakit memang ada, tetapi saya tetap berusaha mengikuti kegiatan seperti biasa. Dari situlah saya belajar bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti. Mengaji, wudhu, hingga shalat saya lakukan dengan satu tangan, sambil menahan perih dan malu.
Kejadian itu menjadi cerita viral di pengajian. Teman-teman sering mengingatnya dengan tawa, memberi saya julukan-julukan yang membuat kesal sekaligus menghibur. Sejak tangan saya diperban dan belum bisa digerakkan, saya kesulitan melakukan banyak hal, termasuk membawa motor karena daging tangan saya belum tumbuh sempurna. Namun di balik itu, saya justru merasakan perhatian dan kepedulian yang lebih dari teman-teman sekitar.
Malam-malam di kobong menjadi bagian yang paling saya rindukan. Kami tidur beralaskan tikar tipis, berbincang sebelum terlelap, dan tertawa tanpa alasan yang jelas. Di luar, dunia diliputi rasa takut oleh pandemi, tetapi di dalam kobong, kami menemukan rasa aman melalui kebersamaan dan doa-doa yang kami panjatkan bersama.
Seiring waktu, luka di tangan saya perlahan mengering. Bekasnya masih tertinggal hingga kini, menjadi pengingat akan satu kejadian yang tak akan terlupakan. Ketika saya kembali ke sekolah dan menceritakan kejadian itu di depan teman-teman SMA, mereka tertawa mendengarnya, dan saya ikut tertawa. Cerita memalukan itu berubah menjadi kenangan yang justru saya syukuri.
Pandemi akhirnya berlalu. Aktivitas kembali normal, dan kobong tidak lagi seramai dulu. Teman-teman satu per satu melanjutkan hidupnya masing-masing. Ada yang jarang mengaji, ada yang pindah, ada pula yang hanya tersisa dalam ingatan. Namun semua kenangan itu tetap hidup, tersimpan rapi di hati.
Kini, ketika mengingat masa COVID-19 di kobong, yang tersisa bukan rasa sakit atau malu, melainkan rasa syukur. Saya bersyukur pernah jatuh dan bangkit, pernah terluka dan dikuatkan, serta pernah bersama dalam masa sulit. Andai waktu bisa diulang, saya tidak ingin menghapus kejadian itu—karena dari sanalah saya belajar arti kebersamaan, kesabaran, dan makna tumbuh menjadi manusia yang lebih kuat.













Tinggalkan Balasan