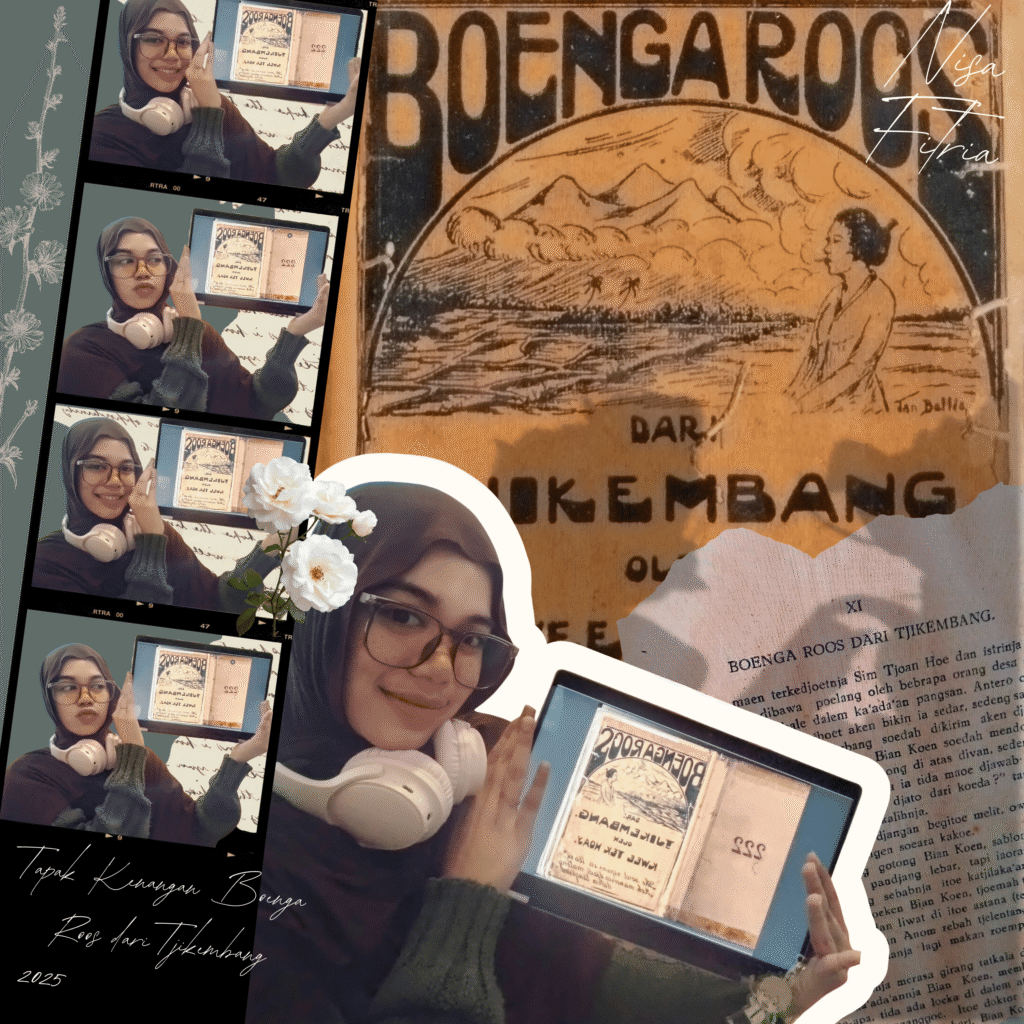
[Sumber gambar: Dokumentasi penulis]
Penulis: Nisa Fitria
Pada suatu masa ketika kata-kata ditulis dengan kesabaran, sebuah perasaan disimpan dalam diam, Boenga Roos dari Tjikembang lahir sebagai sebuah kisah yang tidak sekadar ingin dibaca, melainkan ingin dikenang. Novel karya Kwee Tek Hoay ini pertama kali menghirup udara sastra pada tahun 1927, di Batavia— sebuah kota yang kala itu menyimpan banyak cinta yang tak pernah benar-benar menemukan tempat pulang. Ia hadir bukan sebagai cerita yang tergesa, melainkan sebagai jejak perasaan yang tumbuh perlahan.
Sebelum menjelma menjadi novel, Boenga Roos dari Tjikembang mula-mula diciptakan sebagai naskah drama atas pesanan Tuan Ong Tjoei Hong, untuk dipentaskan oleh Union Dalia Opera. Dari panggung itulah kisah ini pertama kali bernapas, tetapi takdir rupanya tidak berhenti pada cahaya lampu dan tirai pertunjukan itu saja. Cerita ini kemudian menyeberang ke halaman-halaman mingguan Panorama, hadir secara berkala selama hampir dua bulan— seolah ingin menyapa pembacanya sedikit demi sedikit, memberi waktu bagi rasa untuk tumbuh serta bagi luka untuk dikenal. Hingga akhirnya, pada tahun yang sama, kisah ini dihimpun dan diterbitkan oleh Drukkerij Hoa Siang In Kok di Batavia, hadir menjadi sebuah novel yang tak lagi sekadar dipentaskan atau dibaca sepintas, melainkan menetap, perlahan, dalam ingatan sastra Indonesia.
***
Di sebuah perkebunan karet bernama Goenoeng Moelia, cinta pernah tumbuh dalam diam. Oh Aij Tjeng, seorang administrateur muda keturunan Tionghoa, hidup bersama Marsiti— perempuan Sunda yang menjadi nyai sekaligus tempat Aij Tjeng menambatkan seluruh perasaannya. Pada Marsiti, Aij Tjeng percaya bahwa kesetiaan dapat bertahan dari apa pun. Namun dunia tidak selalu memberi ruang bagi cinta yang lahir di luar kehendak kekuasaan dan adat. Ketika Liok Keng Djim, bos perkebunan, meminta Aij Tjeng menikahi putrinya, Gwat Nio, dan ayahanda Aij Tjeng turut memaksanya, Marsiti pun disingkirkan dari kehidupan yang pernah ia anggap rumah. Ia pergi, membawa sunyi, dan tak pernah kembali.
Pernikahan dengan Gwat Nio perlahan menumbuhkan cinta baru dalam diri Aij Tjeng— cinta yang terasa serupa, bahkan lebih halus, hingga kenangan akan Marsiti memudar tanpa disadari. Di sini takdir menyimpan ironi yang kejam. Menjelang ajalnya, Liok Keng Djim mengatakan rahasia yang terlambat diungkapkan: ”—Tapi berbareng dengen itoe akoe bikin anakkoe jang soeloeng, Marsiti, djadi tjilaka…” Marsiti adalah putrinya sendiri, buah dari masa lalu yang tak pernah diakui. Penyesalan datang ketika segalanya telah hilang— Marsiti telah meninggal, dan rahasia lain ikut terkubur bersama kematian orang-orang yang menyimpannya. Yang tertinggal hanyalah luka, dan kesunyian yang tak lagi bisa diperbaiki.
Waktu berlalu delapan belas tahun. Dari pernikahan Aij Tjeng dan Gwat Nio lahirlah Lily, gadis cantik yang hidup dalam bayang-bayang kematian, seolah sejak awal ia tahu bahwa hidupnya tidak akan panjang. Tunangannya, Sim Bian Koen, mencintainya dengan segenap jiwa, namun kehilangan Lily menyeretnya ke tepi keputusasaan. Hingga suatu hari, di desa Cikembang, ia melihat sosok yang mustahil— Lily, hidup, berlari, menolak disentuh. Dari perjumpaan ganjil itulah tabir masa lalu perlahan tersibak: gadis itu bukan Lily, melainkan Roosminah, putri Aij Tjeng dan Marsiti, yang dibesarkan diam-diam oleh Tirta. Karena kecantikannya, ia dikenal sebagai Boenga Roos dari Tjikembang.
”dan ia ada gadis jang paling tjantik dan eilok sendiri di ini desa hingga orang banjak namaken ia ”Boenga Roos dari Tjikembang” hlm. 62
Kemudian, pada akhirnya dengan identitas yang dipertukarkan, Roosminah menikah dengan Bian Koen dalam pesta megah, disaksikan bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh roh Marsiti— cinta lama yang tak pernah benar-benar pergi. Lima tahun kemudian, ketika keluarga itu kembali berkumpul, sebuah bunga dari pohon yang pernah ditanam Marsiti hadir sebagai penanda bahwa cinta yang disingkirkan, dilupakan, bahkan dikuburkan, tetap menemukan caranya sendiri untuk hidup. Hidup menjadi tapak kenangan yang tak akan pernah terhapus oleh waktu.
***
Kelebihan Boenga Roos dari Tjikembang terletak pada caranya memperlakukan cinta sebagai sesuatu yang tidak pernah sederhana. Cinta di dalam novel ini tidak datang untuk menyelamatkan, melainkan untuk diuji— oleh adat, oleh kuasa, oleh waktu. Marsiti dicintai bukan untuk dimenangkan, tetapi untuk ditinggalkan dengan utuh. Dalam kesetiaannya yang diam, pembaca menemukan bentuk cinta yang paling menyakitkan sekaligus paling murni: cinta yang rela hilang agar yang dicintai dapat tetap hidup.
Kwee Tek Hoay menulis tokoh-tokohnya dengan kesadaran bahwa manusia jarang benar-benar jahat atau sepenuhnya benar. Oh Aij Tjeng adalah jiwa yang terbelah, berdiri di antara hasrat dan kewajiban, antara suara hati dan tekanan dunia. Ia tidak memilih dengan kejam, tetapi menyerah—dan justru di sanalah tragedinya bermula. Novel ini tidak menghakimi, melainkan membiarkan pembaca menyusuri lorong batin tokohnya, menyaksikan bagaimana keputusan yang tampak masuk akal perlahan berubah menjadi luka yang tak tersembuhkan.
Lebih dari kisah asmara, Boenga Roos dari Tjikembang adalah potret sunyi tentang dunia kolonial yang bertumpu pada ketimpangan. Perempuan pribumi hadir sebagai cinta yang diinginkan, tetapi tidak pernah sepenuhnya diakui. Marsiti dicintai, namun tidak dipertahankan, tak juga dibutuhkan, dan sangat mudah disingkirkan. Dalam diamnya, novel ini menyimpan kritik sosial yang getir—tentang kuasa, tentang darah, tentang siapa yang berhak tinggal dan siapa yang harus pergi tanpa jejak.
Keindahan novel ini juga tumbuh dari struktur ceritanya yang berlapis waktu. Cinta tidak berhenti pada satu generasi, melainkan menjelma kembali dalam rupa lain. Lily dan Roosminah menjadi bayang-bayang masa lalu yang berjalan di masa kini, membuktikan bahwa ingatan tidak pernah mati, hanya berpindah tubuh. Boenga roos, mawar—menjadi lambang yang lembut sekaligus kejam. Ia mekar dengan indah, tetapi selalu menyimpan duri. Dan dari simbol itulah, cerita ini menemukan denyutnya yang paling lirih.
Namun, sebagaimana mawar yang terlalu sempurna dapat terasa artifisial, novel ini pun tidak sepenuhnya luput dari cela. Beberapa simpul cerita terikat oleh kebetulan yang terlalu rapi, seolah takdir bekerja dengan tangan yang terlalu terlihat. Rahasia besar terungkap bukan melalui pergulatan panjang, melainkan melalui peristiwa yang datang tiba-tiba. Bagi pembaca hari ini, hal itu dapat terasa mengurangi kedalaman realitas yang sedang dibangun.
Tokoh perempuan dalam novel ini, meski menjadi pusat emosi cerita, kerap dibiarkan larut dalam kepasrahan. Marsiti mencintai tanpa syarat dan hampir tanpa suara. Ia menerima nasib tanpa perlawanan, seolah penderitaan adalah satu-satunya bentuk kesetiaan yang diizinkan baginya. Pembacaan ini membuka ruang kritik: bahwa perempuan lebih sering dijadikan simbol pengorbanan ketimbang subjek yang berhak memilih jalan hidupnya sendiri.
Nada melodrama yang terus mengalun juga menjadi beban tersendiri. Kesedihan hadir bertubi-tubi, nyaris tanpa jeda untuk bernapas. Akhir cerita yang penuh keindahan dan pemulihan pun dapat terasa terlalu rapi— seolah luka-luka panjang akhirnya ditutup dengan bunga dan perayaan. Mungkin saja, justru di situlah sikap pengarang menumbuhkan sebuah keyakinan lirih bahwa cinta, betapapun dilukai, pantas diberi kesempatan untuk menemukan bentuk kebahagiaan, meski cinta itu datang terlambat.
***
Pada akhirnya, Boenga Roos dari Tjikembang tidak hanya lahir dari khalayan, tetapi dari sebuah getar perasaan yang sederhana: sebuah lagu. Lirik melankolis If Those Lips Could Only Speak— atau yang oleh Kwee Tek Hoay dikenang sebagai Mimi d’Amour— mengalirlah renungan tentang kata-kata yang tak sempat terucap, tentang cinta yang terlanjur dibungkam oleh keadaan. Dari lagu itulah, kisah ini tumbuh, menjelma menjadi “komedi sedih” yang tidak pernah benar-benar ingin menghibur, melainkan mengajak pembacanya larut dalam perasaan kehilangan yang sunyi.
Maka ketika novel ini berakhir, yang tersisa bukanlah kepastian, melainkan hatiku yang menggantung— seperti lagu yang berhenti tepat sebelum bait terakhir. Boenga Roos dari Tjikembang mengajakku percaya bahwa ada cinta yang terlalu dalam untuk selesai, terlalu sunyi untuk dilupakan. Ia tinggal sebagai tapak kenangan, sebagai mawar yang terus mekar di ingatan, mengingatkan kita bahwa jika bibir itu dapat berbicara, barangkali yang terucap hanyalah satu hal: bahwa cinta, meski dikubur oleh waktu, selalu menemukan jalan untuk kembali.


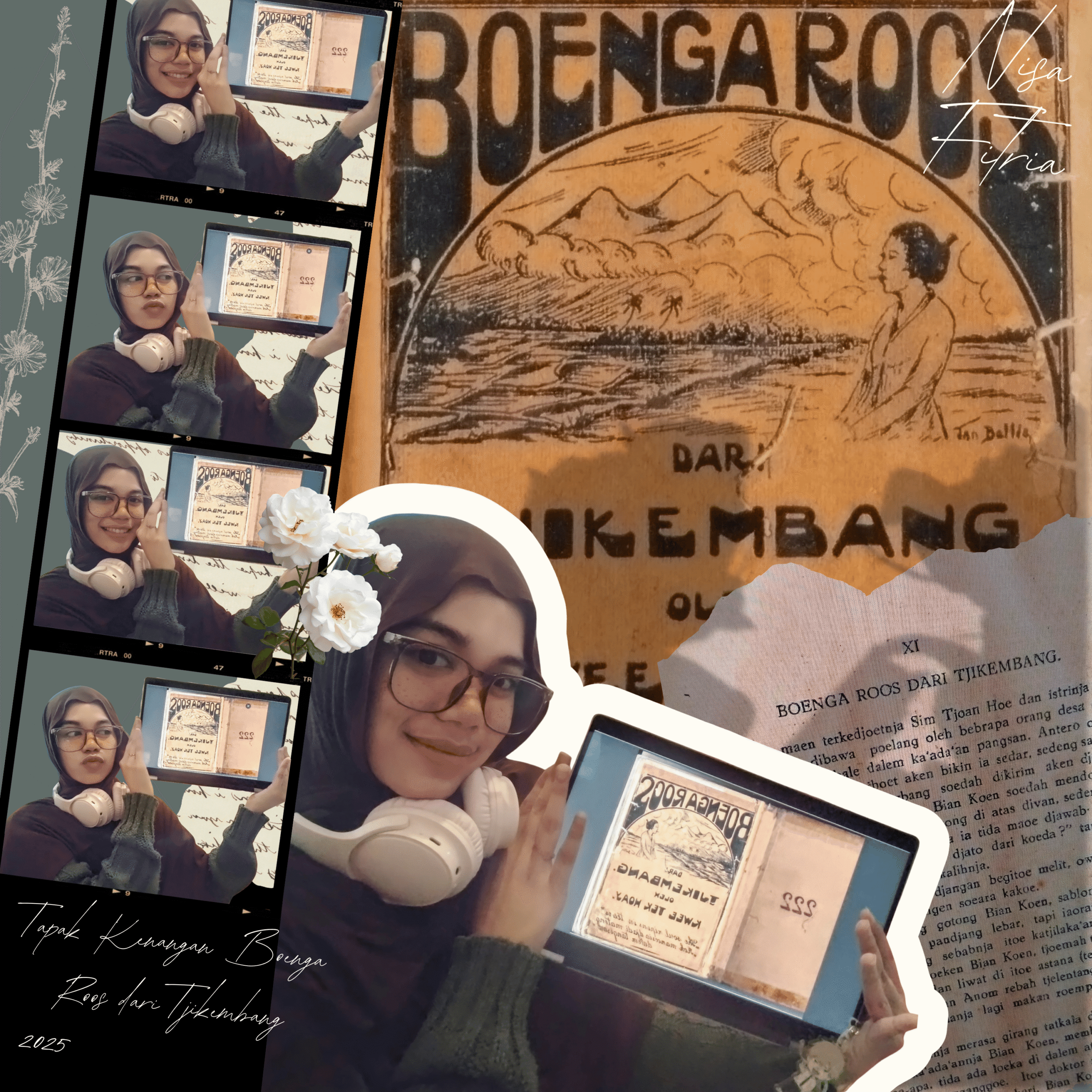










Tinggalkan Balasan