
[Sumber gambar: https://ameera.republika.co.id/]
Penulis: Heri Isnaini
Ada nama yang sekadar orang sebut sebagai alamat. Tetapi ada nama yang bagi saya adalah rumah, adalah asal-usul, adalah denyut yang tidak pernah benar-benar pergi, “Subang”. Subang, bagi saya, bukan sekadar kabupaten di utara Jawa Barat. Saya lahir dan tumbuh di Ciasem, dan setiap kali menyebut “Subang”, ada sesuatu yang bergetar lebih dalam daripada sekadar pengetahuan sejarah. Ia adalah tanah yang saya pijak sejak kecil, sawah yang saya lihat menguning, jalan pantura yang saya saksikan tak pernah benar-benar tidur.
Bagi saya, Subang bukan cuma wilayah administratif, ia adalah simpul ingatan pribadi: tempat legenda, iman, kerja keras, dan jejak kekuasaan bertemu dalam kehidupan sehari-hari. Nama itu seperti Sungai Ciasem yang mengalir tak jauh dari ruang batin saya sendiri. Dari luar ia mungkin tampak tenang, biasa saja. Tetapi bagi saya, ia menyimpan arus kenangan, sejarah, dan rasa memiliki yang tidak sederhana.

Dalam ingatan kolektif masyarakat Sunda, Subang mula-mula adalah nama seorang perempuan, Nyai Subang Larang. Ia hidup kira-kira di abad ke-15, disebut sebagai perempuan Muslim yang cerdas, lembut, dan teguh keyakinannya. Ketika ia dipersunting oleh Prabu Siliwangi, raja besar Kerajaan Pajajaran, peristiwa itu bukan sekadar kisah asmara istana. Ia adalah perjumpaan dua dunia, Hindu-Buddha yang mapan dan Islam yang sedang tumbuh di tanah Sunda.
Saya selalu membayangkan adegan itu dengan imajinasi yang tenang, bahwa ada seorang raja besar dengan kekuasaan yang penuh, lalu terpikat oleh lantunan ayat suci dari seorang perempuan yang tidak meninggalkan keyakinannya. Di sana ada negosiasi, ada toleransi, dan ada kehalusan sikap. Subang Larang bukan tokoh yang meledak-ledak, ia justru kuat dalam kelembutannya. Ia mendidik anak-anaknya dengan nilai agama, menanamkan etika, membentuk karakter. Maka wajar jika namanya melekat dalam kebanggaan masyarakat. Ia bukan sekadar figur sejarah, melainkan simbol moralitas dan kecantikan batin.
Ketika nama “Subang” dipercaya bersumber dari dirinya, saya melihatnya sebagai pilihan kultural. Seakan masyarakat berkata, “Kami ingin dikenal dari nilai yang kami hormati.” Nama itu menjadi penanda bahwa sejarah tidak hanya tentang perang dan takhta, tetapi juga tentang perempuan, pendidikan, dan iman.
Namun, sejarah selalu berlapis. Ia tidak berhenti di babad dan cerita tutur. Memasuki abad ke-19, Subang muncul kembali dalam arsip kolonial, dalam bahasa administrasi dan angka-angka luas tanah. Di sinilah kita bertemu dengan Pamanoekan en Tjiasemlanden, perkebunan raksasa yang membentang luas di wilayah utara. Nama Pieter William Hofland hadir sebagai pengelola besar onderneming itu.

Tanah dibagi menjadi distrik-distrik, yaitu Pamanukan, Ciasem, Pagaden, Segalaherang, dan Subang. Pabrik gula berdiri. Tebu ditanam. Para pekerja didatangkan dari berbagai daerah. Administrasi dijalankan dengan disiplin kolonial. Kampung-kampung tumbuh di sekitar aktivitas ekonomi itu. Subang menjadi pusat yang sibuk, tempat keputusan diambil, tempat orang datang dan menetap.
Di sini, nama Subang bukan lagi gema legenda, melainkan denyut industri. Ia menjadi identitas administratif, menjadi pusat kademangan, menjadi simpul mobilitas sosial. Jika pada abad ke-15 Subang adalah simbol spiritualitas maka pada abad ke-19 ia menjelma simbol ekonomi dan kekuasaan tanah partikelir.
Apakah dua kisah ini saling meniadakan? Bagi saya, tidak. Justru di situlah keindahan sejarah lokal. Subang tidak lahir dari satu sumber tunggal. Ia tumbuh dari dua arus yang berbeda, arus legenda dan arus arsip. Yang satu hidup dalam ingatan lisan, dalam ziarah ke makam, dan dalam cerita orang tua kepada anaknya. Yang lain hidup dalam dokumen, dalam laporan perkebunan, dan dalam peta-peta lama yang mencatat batas wilayah.

Saya membayangkan Sungai Ciasem mengalir melewati semua itu. Ia menyaksikan kisah Nyai Subang Larang yang dituturkan dari generasi ke generasi. Ia juga menyaksikan para buruh menapaki pematang sawah menuju ladang tebu milik perusahaan besar. Sungai itu tidak memilih mana yang lebih benar. Ia hanya mengalir, membawa endapan-endapan waktu, membentuk tanah yang kita pijak hari ini.
Mungkin memang begitu seharusnya kita membaca asal-usul. Bukan untuk menentukan versi mana yang paling sah, melainkan untuk memahami bahwa identitas adalah hasil dialektika panjang. Subang adalah pertemuan antara iman dan industri, antara perempuan dan perkebunan, antara cinta dan kapital. Ia adalah nama yang lahir dari nilai sekaligus dari kerja.
Dan setiap kali kita menyebut “Subang”, tanpa sadar kita sedang memanggil seluruh lapisan sejarah itu sekaligus. Kita menyebut seorang perempuan yang lembut namun teguh. Kita menyebut tanah yang pernah digarap dengan sistem kolonial. Kita menyebut sungai yang setia mengalir, mengingat semuanya, tanpa pernah benar-benar lupa.
Bandung, 18 Februari 2026




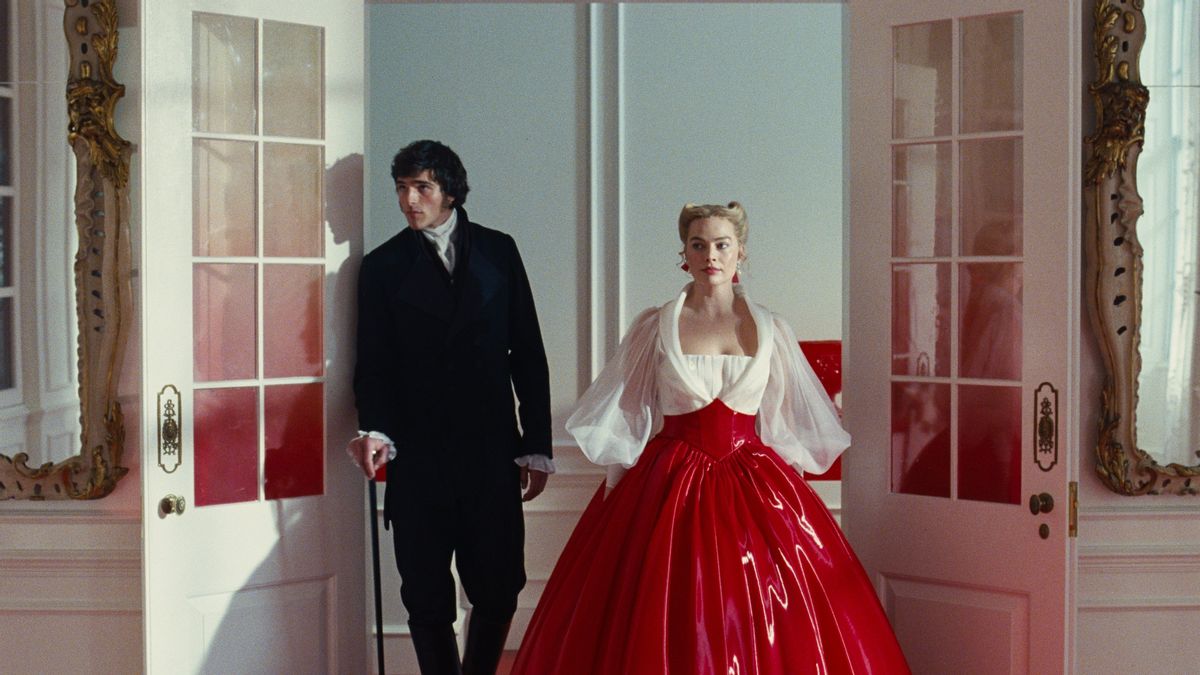



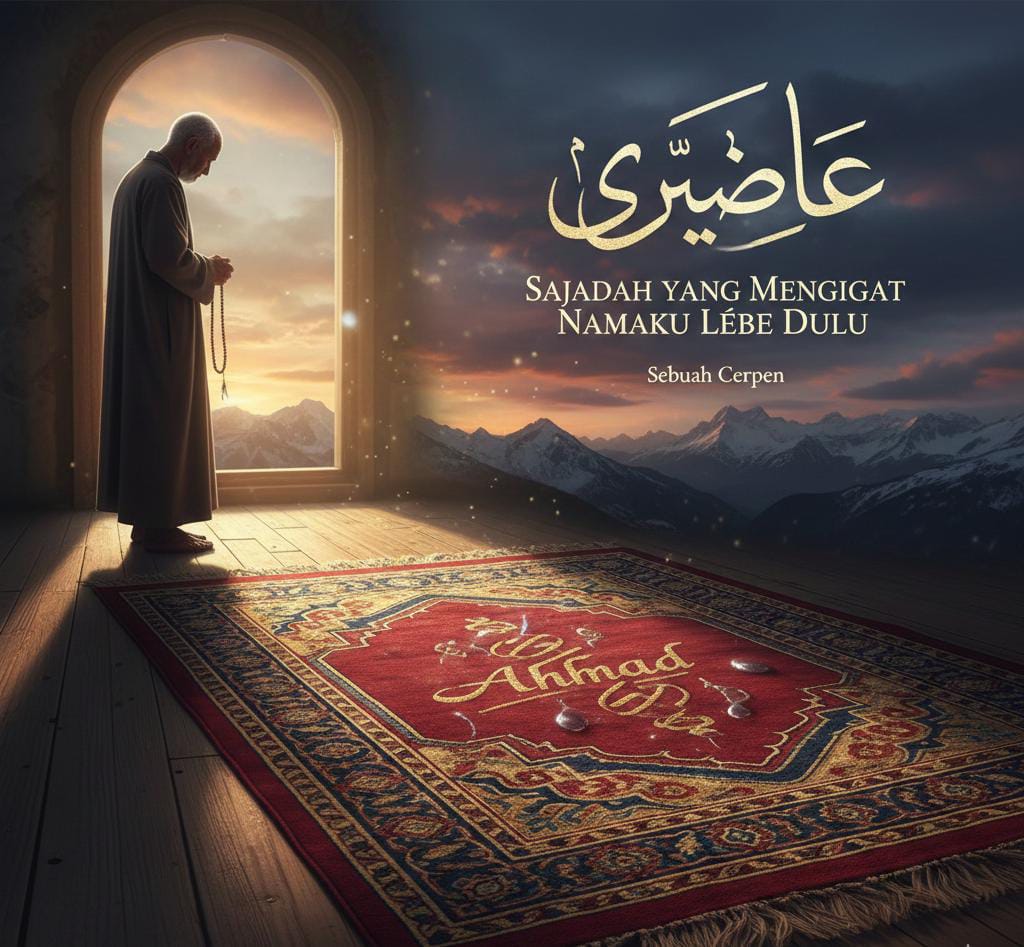


Tinggalkan Balasan