
[Sumber gambar: “Praying” karya Mihaela Ionescu]
Penulis: Heri Isnaini
Puasa dan puisi sama-sama dimulai dari kekosongan. Dalam puasa, tubuh dikosongkan dari makan dan minum. Dalam puisi, halaman dikosongkan dari kebisingan kata-kata yang tidak perlu. Keduanya bukan tindakan pasif, melainkan disiplin aktif. Ada niat, ada kesadaran, ada pilihan untuk tidak menuruti dorongan keserakahan.
Puasa mengajarkan kita bahwa tidak semua rasa harus segera dipenuhi. Puisi mengajarkan bahwa tidak semua kata harus segera dijelaskan. Dalam puasa, lapar ditahan agar makna hidup terasa. Dalam puisi, kata ditahan agar makna tidak tumpah ruah dan kehilangan kedalamannya.
Jika puasa adalah laku tubuh, puisi adalah laku bahasa. Seorang penyair tahu, kata yang berlebihan bisa merusak getaran. Karena itu, ia memilih, menyaring, dan menghapus. Ia membiarkan jeda bekerja. Dalam teori estetika, jeda bukan kekosongan yang kosong, melainkan ruang resonansi. Demikian pula dalam puasa, lapar bukan sekadar absennya makanan, tetapi hadirnya kesadaran.
Puisi-puisi Sapardi Djoko Damono sering bergerak dalam kesenyapan seperti itu. Ia tidak meledak-ledak. Ia lirih. Namun justru dalam kelirihan itu saya menemukan intensitas. Mirip orang berpuasa yang tidak banyak bicara tentang laparnya, tetapi menghadirkan kenikmatan batin dalam jiawanya.
Puasa juga melatih sensitivitas. Ketika perut kosong, indra terasa lebih peka. Bau makanan lebih tajam, waktu terasa lebih panjang, dan suara lebih jernih. Kepekaan inilah yang juga dibutuhkan dalam puisi. Penyair hidup dari kepekaan-kepekaan terhadap detail, terhadap perubahan cahaya, terhadap getar batin yang nyaris tak terdengar.
Menariknya, puasa dan puisi sama-sama menunda klimaks. Dalam puasa, kenikmatan makan ditangguhkan hingga Magrib. Dalam puisi, makna sering ditangguhkan hingga larik terakhir, bahkan terkadang hingga pembacaan kedua atau kesekian. Penundaan itu bukan penyiksaan, melainkan strategi pendalaman.
Secara etis, keduanya juga berkaitan. Puasa mengajarkan pengendalian diri, yaitu menahan amarah, menahan gosip, dan menahan kesombongan. Puisi yang baik pun menuntut integritas, untuk tidak manipulatif dan tidak sekadar sensasional. Ia lahir dari perenungan, bukan dari kegaduhan.
Mungkin itulah sebabnya banyak penyair merasa Ramadan sebagai bulan yang subur. Ada ritme kontemplatif yang mendukung penciptaan. Malam lebih panjang, doa lebih khusyuk, dan kesunyian lebih terasa. Dalam suasana seperti itu, kata-kata tidak berteriak, mereka berbisik.
Puasa dan puisi pada akhirnya sama-sama mengajarkan ekonomi hasrat dan ekonomi bahasa. Mengurangi agar makna bertambah. Menahan agar kedalaman tumbuh. Sebab kadang-kadang, yang paling penting dalam hidup bukanlah apa yang kita konsumsi atau apa yang kita ucapkan, melainkan apa yang sanggup kita tahan.
Bandung, Februari 2026



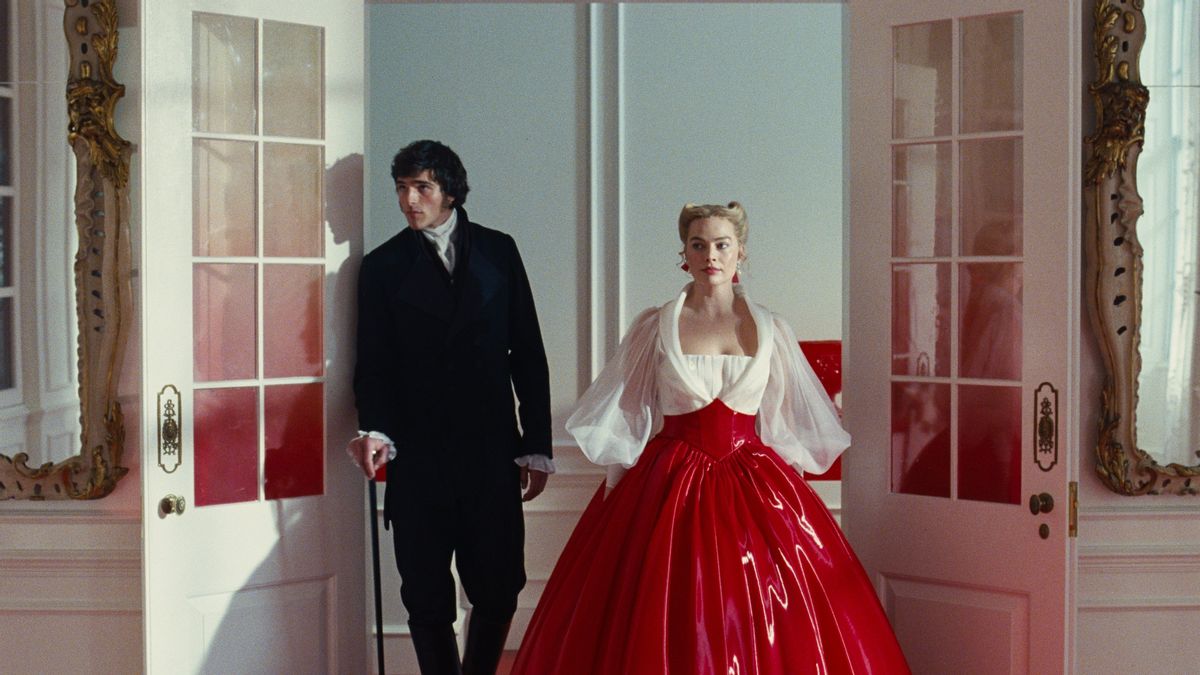



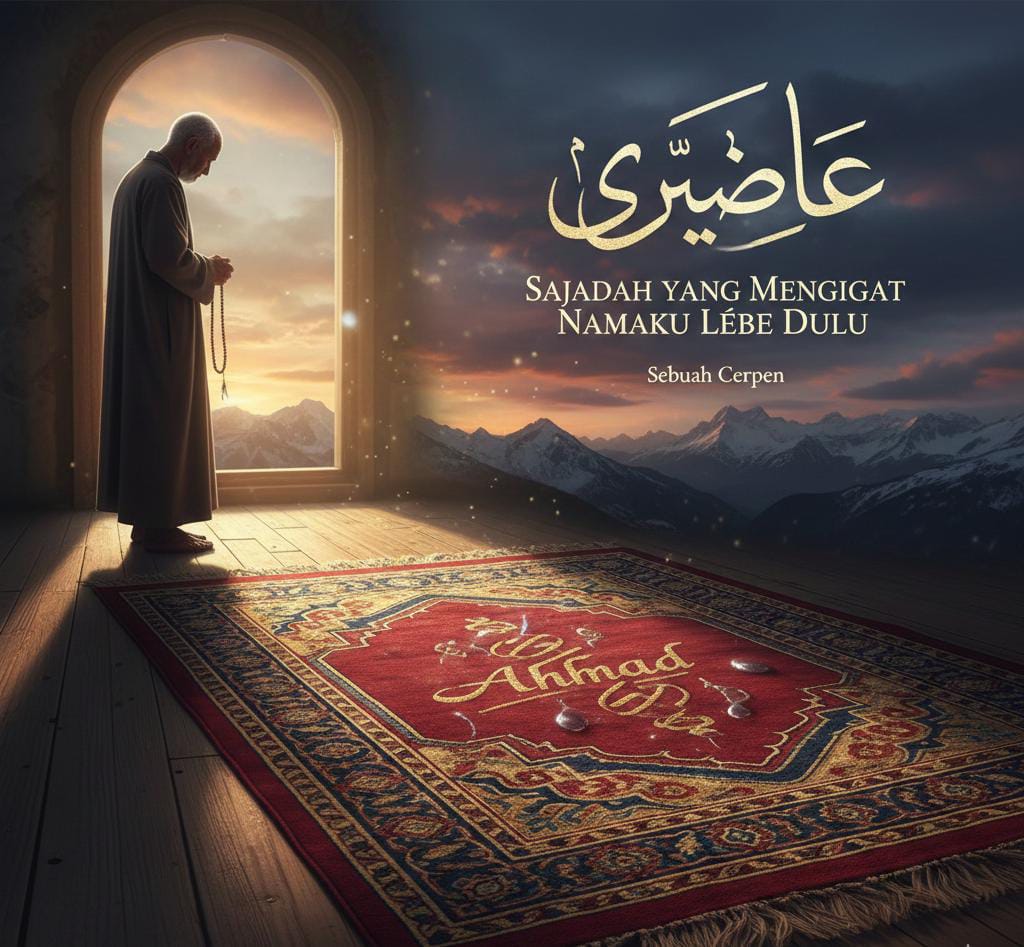



Tinggalkan Balasan