
[Sumber gambar: Gemini AI]
Penulis: Amhar
Ada satu hal yang belakangan saya sadari bahwa kenikmatan sering kali tidak lahir dari kelimpahan, melainkan dari keterbatasan.
Bayangkan seseorang yang sangat menyukai durian. Ia menunggu musimnya, berburu ke pinggir jalan, memilih dengan hati-hati, lalu membuka kulitnya dengan harap-harap cemas. Ada degup kecil di dada sebelum daging buah itu menyentuh lidah. Itulah kenikmatan.
Sekarang bayangkan orang yang memiliki kebun durian sendiri. Pohonnya puluhan. Buahnya ratusan. Setiap hari bisa makan sepuasnya. Awalnya mungkin terasa istimewa. Namun lama-lama, rasa itu menjadi biasa. Tidak ada lagi debar penantian. Tidak ada lagi momen yang ditunggu-tunggu. Yang berlimpah sering kali kehilangan kejutan.
Dari situ saya belajar, kenikmatan ternyata punya alamat yang unik, “ia tinggal di batas.”
Coba lihat hari akhir pekan. Siapa yang paling menikmatinya? Biasanya mereka yang bekerja keras dari Senin sampai Jumat. Mereka yang menghitung hari, yang menanti Sabtu seperti menanti kabar baik. Bagi mereka, akhir pekan adalah ruang bernapas. Ada rasa lega, ada rasa bebas.
Sebaliknya, orang yang sejak Senin hingga Minggu memiliki waktu luang tanpa batas, mungkin tak lagi merasakan getar itu. Ketika setiap hari terasa sama, maka “akhir pekan” kehilangan maknanya. Tanpa batas antara lelah dan jeda, istirahat menjadi hambar.
Hidup pun demikian. Ia terasa berharga justru karena ada garis yang tak bisa kita lewati, yakni kematian. Kita menghargai waktu karena ia tidak abadi. Kita mencintai pertemuan karena ada kemungkinan perpisahan. Jika hidup tanpa batas, mungkin kita akan menunda segalanya. Kita tidak akan tergesa untuk memeluk, meminta maaf, atau mengatakan cinta.
Batas membuat sesuatu bernilai.
Puasa adalah contoh yang paling nyata. Seharian menahan lapar dan haus, menahan amarah, menahan keinginan. Ada perjuangan sunyi sejak fajar hingga senja. Lalu azan Magrib berkumandang. Seteguk air terasa seperti anugerah yang tak terlukiskan. Sepotong kurma terasa lebih manis dari biasanya.
Mengapa? Karena ada batas yang kita jaga. Ada rasa yang kita tahan.
Bagi orang yang tidak berpuasa, waktu berbuka hanyalah jam makan biasa. Tidak ada ledakan syukur, tidak ada keharuan kecil di dalam dada. Kenikmatan itu hanya benar-benar dipahami oleh mereka yang menahan diri sepanjang hari. Ada bahagia yang sulit dijelaskan dengan kata-kata dan ia hanya bisa dirasakan.
Maka ketika kita merasa sesuatu tidak lagi nikmat, mungkin bukan karena ia kurang. Bisa jadi justru karena ia terlalu banyak. Terlalu mudah. Terlalu tersedia.
Barangkali yang kita butuhkan bukan tambahan, melainkan batas.
Karena pada akhirnya, kenikmatan bukan soal memiliki segalanya. Ia soal jarak antara ingin dan dapat. Soal jeda antara usaha dan hasil. Soal lapar sebelum kenyang. Soal rindu sebelum temu.
Dan selama hidup masih memiliki batas, selama ada yang kita nantikan dan perjuangkan, di situlah kenikmatan akan terus menemukan rumahnya.






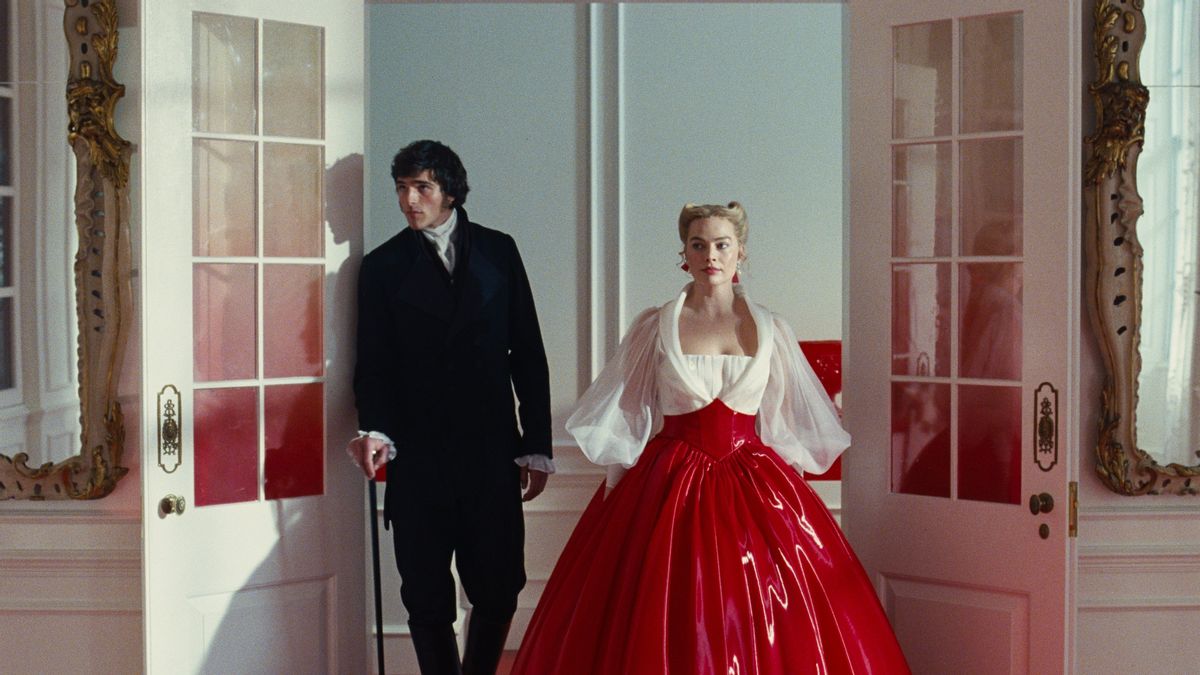



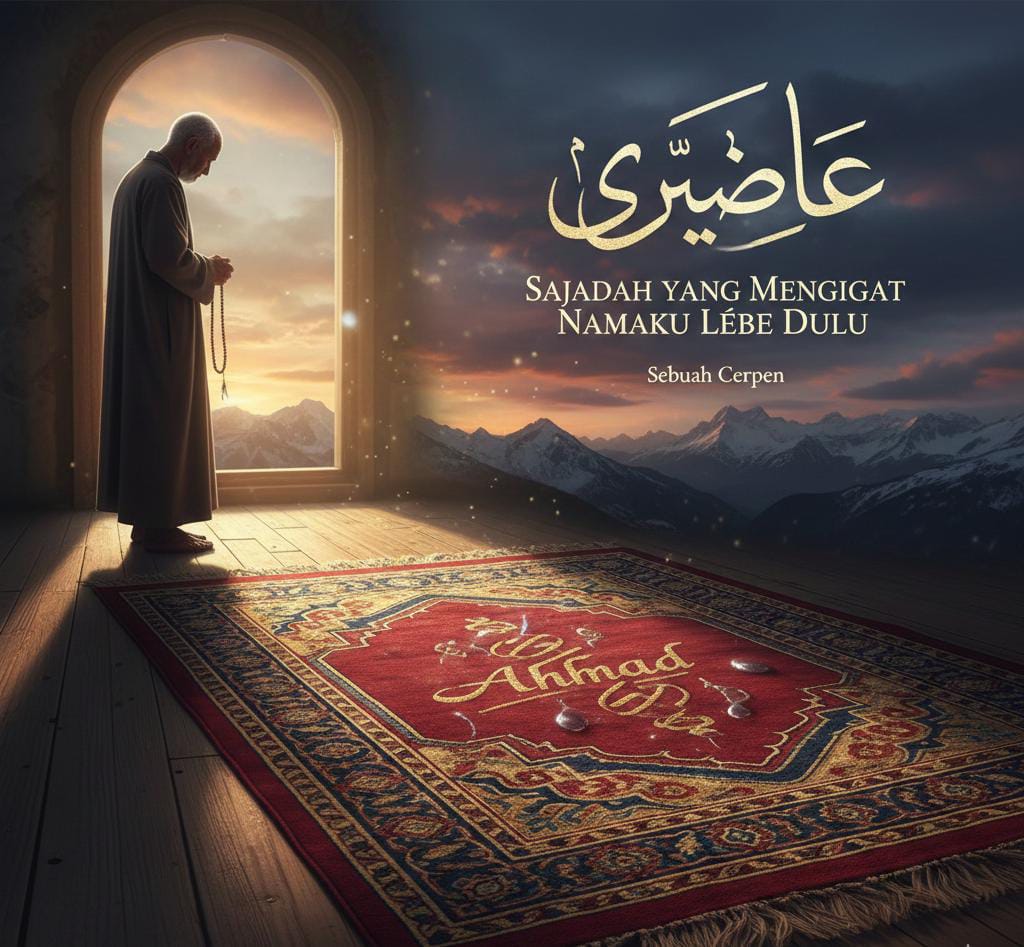
Tinggalkan Balasan