
[Sumber gambar: https://assets.pikiran-rakyat.com/]
Penulis: Heri Isnaini
Dalam kajian sastra, film, yaitu proses mengalihwahanakan cerita dari teks ke layar dikenal sebagai ekranisasi. Ia bukan sekadar memindahkan cerita, tetapi menafsir ulang makna sesuai medium dan zamannya. Film Penunggu Rumah: Buto Ijo tidak mengadaptasi legenda Timun Mas dengan cara menyalin alur atau tokohnya secara utuh, melainkan mengekstrak inti temanya tentang janji, ketakutan, dan konsekuensi. Dari sinilah dongeng lama itu tumbuh dewasa berubah dari kisah pelarian anak-anak menjadi horor batin orang dewasa, yang justru terasa lebih dekat dengan pengalaman hidup kita hari ini.
Meski tampil dalam bentuk dan nuansa yang berbeda, legenda Timun Mas dan film Penunggu Rumah: Buto Ijo bertemu pada satu simpul yang sama, yakni janji yang lahir dari keterdesakan seorang ibu. Dalam keduanya, hasrat untuk mempertahankan hidup dan masa depan anak menjadi alasan utama terjadinya perjanjian dengan kekuatan di luar manusia. Baik dalam dongeng maupun film, konflik tidak pernah benar-benar berpusat pada sosok raksasa, melainkan pada keputusan manusia di titik paling rapuhnya. Kesamaan inilah yang membuat adaptasi terasa sahih karena yang dipindahkan bukan sekadar cerita, melainkan denyut etis dan emosional yang sejak awal telah hidup dalam legenda Timun Mas.
Dalam legenda Timun Mas, segalanya berawal dari sebuah permohonan yang lahir dari keterdesakan. Seorang perempuan menginginkan anak, lalu datang Buto Ijo dengan syarat yang kelak menagih harga.
“Anak itu kelak menjadi milikku.”
(Legenda Timun Mas)
Kalimat itu sederhana, nyaris datar. Tetapi di sanalah benih horor ditanam “Janji yang dibuat saat manusia sedang lemah.”
Film Penunggu Rumah: Buto Ijo membaca ulang kalimat itu dengan kacamata zaman sekarang. Janji tersebut tidak lagi berdiri sebagai dongeng hitam-putih, melainkan sebagai konflik batin orang dewasa terutama seorang ibu yang pernah memilih bertahan hidup dengan cara yang ia kira bisa dilupakan.
Dalam film, Srini tidak pernah menyebut kata “perjanjian” secara gamblang. Namun satu dialognya terasa seperti pengakuan yang bocor pelan-pelan:
“Aku pikir, semua itu sudah selesai.”
(Penunggu Rumah: Buto Ijo, 2026)
Kalimat ini terasa sangat manusiawi. Kita semua pernah berpikir seperti itu bahwa waktu bisa menghapus kesalahan, bahwa diam bisa menjadi penebus. Film ini lalu menghadirkan Buto Ijo sebagai bantahan paling keras terhadap asumsi tersebut.

Dari Dongeng Pelarian ke Horor Penantian
Dalam legenda, Timun Mas berlari. Ia dilempari biji mentimun, jarum, garam, dan terasi simbol kecerdikan dan bantuan alam.
“Timun Mas berlari sekuat tenaga, sementara raksasa itu tertahan oleh jebakan-jebakan alam.”
(Legenda Timun Mas)
Film ini menghapus adegan pelarian itu. Tidak ada kejar-kejaran panjang. Tidak ada raksasa yang selalu muncul jelas di layar. Sebaliknya, Buto Ijo menunggu. Ia hadir lewat gangguan kecil, lewat ketakutan anak, lewat rumah yang tak lagi ramah.
Dalam salah satu adegan kunci, Srini berkata dengan suara hampir menyerah:
“Kalau memang harus dibayar, jangan anakku.”
(Penunggu Rumah: Buto Ijo, 2026)
Di titik inilah nilai adaptif film ini terasa kuat. Dongeng Timun Mas dipindahkan dari cerita tentang anak yang diselamatkan, menjadi kisah tentang ibu yang harus bertanggung jawab. Konflik bergeser dari fisik ke moral, dari luar ke dalam.
Anak dan Warisan Ketakutan
Dalam legenda, Timun Mas sadar bahwa ia diburu. Dalam film, anak justru tidak tahu apa-apa, tetapi menanggung akibatnya. Ini pembacaan yang pahit, namun jujur terhadap kenyataan hidup.
Film ini seolah berkata:
trauma tidak selalu diwariskan lewat cerita, tetapi lewat keheningan.
Buto Ijo dalam film bukan hanya makhluk mitologis, melainkan simbol dari utang batin yang diwariskan lintas generasi. Ia bukan sekadar penjahat, tetapi ia adalah konsekuensi.
Nilai Adaptif: Folklor yang Bertumbuh
Adaptasi film ini patut dicatat bukan karena kesetiaannya pada detail cerita lama, melainkan karena keberaniannya menggeser makna tanpa mengkhianati ruh.
Legenda Timun Mas mengajarkan kecerdikan untuk bertahan.
Film Penunggu Rumah: Buto Ijo mengajarkan keberanian untuk mengakui.
Jika dongeng berkata, “Larilah agar selamat,”
film ini berbisik, “Hadapilah agar selesai.”
Itulah nilai adaptif terpentingnya: folklor tidak dibekukan sebagai nostalgia, tetapi dijadikan cermin bagi manusia modern yang hidup dengan utang janji, rasa bersalah, dan trauma yang sering disembunyikan di balik kesibukan.
Dan mungkin benar Buto Ijo tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu, sampai seseorang cukup berani untuk berkata, “Aku tidak akan lari lagi.”
Penutup: Janji, Dosa, dan Pulang
Dalam pembacaan sufistik, janji bukan sekadar kontrak, melainkan ikatan batin antara manusia dan kebenaran yang ia sadari atau yang sengaja ia abaikan. Setiap janji yang dilanggar tidak menghilang, tetapi berubah rupa menjadi kegelisahan, ketakutan, dan rasa bersalah yang menetap diam-diam.
Buto Ijo, dalam tafsir ini, bukan semata makhluk gaib. Ia adalah nafsu dan ego masa lalu yang belum ditundukkan, dosa yang belum diakui, dan kesalahan yang belum dipulangkan kepada asalnya. Ia menunggu bukan karena dendam, melainkan karena pengakuan belum terjadi.
Dalam sufisme, penyelesaian tidak terletak pada pelarian, melainkan pada muhasabah, yaitu keberanian menengok ke dalam diri dan berkata jujur pada Tuhan dan pada diri sendiri. Di titik itulah horor berubah menjadi jalan pulang.
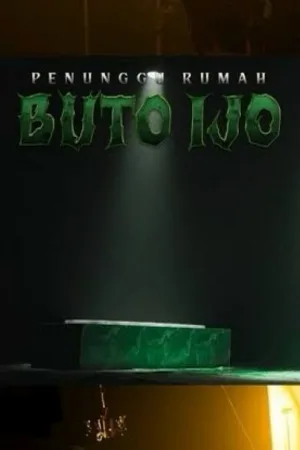
Film Penunggu Rumah: Buto Ijo seakan mengingatkan bahwa rumah paling angker bukanlah bangunan tua di pinggir hutan, melainkan hati yang menyimpan rahasia terlalu lama. Selama janji belum disadari, selama dosa belum diakui, Buto Ijo akan terus menjadi penunggu.
Dan mungkin, yang benar-benar menyelamatkan bukanlah kecerdikan seperti dalam dongeng, melainkan kerendahan hati untuk berkata: “Aku pernah salah, dan aku siap menanggungnya.”
Di situlah Timun Mas versi dewasa menemukan maknanya, bukan sebagai kisah melarikan diri dari raksasa, tetapi sebagai perjalanan jiwa menuju kejujuran dan pulang.
Bandung, 24 Januari 2026













Tinggalkan Balasan